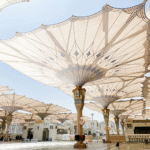Ada hal-hal yang lebih mengejutkan dari listrik mati pas lagi keramas. Salah satunya adalah yang akan aku ceritain ini.
Namaku Lira, 34 tahun. Ibu satu anak, manajer keuangan freelance, dan istri yang cukup percaya diri akan kesetiaan suami. Sampai sebuah hari di bulan Juni yang terlalu tenang itu, ketika Dewa—suamiku yang baru pulang dinas luar kota 16 hari di Makassar—meletakkan kopernya di ruang tamu dengan santai. Seolah tak ada ledakan yang sedang bersiap meletus dari dalamnya.
“Aku mandi dulu, ya. Capek banget,” katanya sambil mencium keningku sekilas.
Aku mengangguk sambil tersenyum, “Mau kopi nanti?”
“Boleh,” sahutnya dari tangga.
Dewa masuk ke kamar mandi. Aku masuk ke kamar membawa kopernya.
Awalnya niatku cuma mau bantu, beresin baju kotor, pisahin laundry dari dokumen kantor. Tapi kebiasaan kepo-an istri, ditambah feeling yang tiba-tiba muncul kayak sinyal WiFi di tempat sepi, membuat tanganku bergerak ke kantong kecil samping koper.
Di sanalah petualangan dimulai.
Pertama, ada struk supermarket. Biasa. Isinya minuman energi, camilan, rokok—standar lelaki dinas. Tapi di bawah daftar, ada satu entri yang bikin otakku freeze: “Fiesta Ultra Thin 2 kotak – Rp 47.600”.
Fiesta. Ini bukan merk nugget!!!
Sebagai ibu rumah tangga yang masih sehat pikirannya dan cukup mengerti merek-merek di dunia perlindungan ekstra, aku tahu itu bukan merek makanan. Itu alat tempur. Tapi bukan buat perang beneran—buat “perang” yang Dewa harusnya lakukan hanya denganku.
Aku tarik napas panjang. Oke. Mungkin ada penjelasan logis. Mungkin dia iseng. Mungkin dibeliin temen. Mungkin… ah, sudahlah. Katanya istri itu harus husnuzon. Tapi sialnya, aku bukan ustazah.
Lanjut ke kantong dalam koper. Dua lembar kertas tebal terlipat rapi. Kuintip pelan.
Hotel Grand Mutiara. Check-in Jumat, check-out Minggu. Dua tamu. Makan malam dua porsi. Signature Romantic Dinner.
Seketika, udara berubah rasa. Dinginnya bukan dari AC, tapi dari ujung jantungku yang mulai mencair karena terbakar.
Dan itu bukan satu struk. Ada dua. Dua akhir pekan. Dua kali makan malam berdua. Dua kali kamar deluxe ocean view.
Dewa bilang dinasnya padat. Tiap hari rapat. Ternyata padatnya bukan karena kerja, tapi karena kegiatan romantis berbayar.
Aku tak langsung marah. Tidak. Terlalu gampang. Aku perempuan dengan martabat. Aku punya cara yang lebih halus—dan lebih menyakitkan.
Sore itu, setelah Dewa selesai mandi dan rebahan di sofa sambil main HP, aku menyiapkan kopi. Tapi bukan itu bagian terbaiknya.
Aku ambil dua struk hotel dan satu struk supermarket itu, lalu kuletakkan manis di tengah meja makan. Seolah mereka hidangan utama.
Aku tak bilang apa-apa. Hanya menyimpan senyum. Sore itu, aku jadi istri terbaik: menyiapkan kopi dan bukti.
Besok paginya, meja makan masih utuh. Struk tetap di tempat. Dan Dewa? Seperti biasa. Sarapan, baca berita, lalu bilang, “Minggu depan harus ke kantor pusat lagi. Cuma tiga hari.”
Tiga hari, katamu?
Aku hampir tertawa. Tapi kutahan.
“Enak ya makanan di Makassar?” tanyaku, santai sambil mengaduk teh.
“Iya, enak. Kalo kamu ikut pasti seneng.”
“Romantic dinner-nya juga enak?”
Dia melirik. “Hah?”
Aku dorong struk ke arahnya. “Signature Romantic Dinner. Dua orang. Hari Sabtu malam. Hotel Grand Mutiara. Sama makanan laut kesukaan kamu.”
Dewa diam. Sepersekian detik.
Aku perhatikan gerak matanya, napasnya yang tertahan, kerongkongan yang menelan ludah. Lalu ekspresi itu muncul—sejenis kombinasi panik, malu, dan sadar dirinya ketahuan.
“Ini… itu… bukan kayak yang kamu pikir…”
“Bukan?” aku menyeringai. “Kamu pikir aku mikir apa?”
Dia terdiam. Lalu mencoba bangkit, mengambil struk, membaca ulang. Seolah itu bisa mengubah isinya.
“Cuma makan doang kok,” katanya akhirnya.
“Dan kondom? Camilan juga?”
“Itu… itu temen kantor. Minta titip.”
“Temennya cewek? Atau kalian arisan?”
Dewa menggaruk kepala. Aku tahu dia sedang mencari jawaban. Sayangnya, dia bukan penulis cerita. Dia bukan aktor. Dia cuma suami panik yang tertangkap tangan.
“Dewa,” kataku pelan, “aku nggak marah.”
Dia menatapku, kaget. “Hah?”
“Aku cuma pengen kamu jujur. Itu aja.”
“Tapi… aku takut kamu marah…”
Aku tertawa. Bukan tawa senang, tapi tawa perempuan yang sudah melewati batas sabar. “Lucu ya, kamu takut aku marah, tapi nggak takut nyakitin aku?”
Dia diam. Lagi.
Beberapa hari berlalu. Rumah sunyi. Aku tak banyak bicara. Tapi Dewa mulai berubah. Tiba-tiba rajin shalat, bantu nyapu, bahkan masak nasi goreng. Katanya mau memperbaiki diri.
Tapi luka itu… tak bisa sembuh semudah itu. Struk-struk itu, walau sudah kubakar, bekasnya menempel di dinding hati.
Suatu malam, aku menulis surat. Bukan surat cinta, tapi bukan surat “cerai” juga. Isinya:
“Dewa,
Kamu tahu kenapa aku nggak langsung marah?
Karena marah itu energi. Dan kamu… sudah nggak layak mendapatkan energi itu dariku. Aku diam karena aku menghargai diriku. Bukan karena kamu pantas dimaafkan.
Aku nggak akan pisah. Tapi aku juga nggak akan pura-pura bahagia.
Jadi kalau kamu mau tetap di sini, ayo benerin semuanya. Tapi ingat, rumah ini bukan tempat kamu istirahat dari kebohongan. Ini tempat kamu bertanggung jawab atasnya.
Kalau kamu nggak bisa, koper itu masih ada. Tinggal kamu isi, dan pergi.
—Lira”
Kusimpan surat itu di meja tempat dulu aku meletakkan struk. Ada keadilan di sana.
Pagi harinya, Dewa membacanya. Matanya merah. Tapi aku tak menangis.
“Lira, aku… nyesel.”
Aku mengangguk. “Nyesel karena ketahuan? Atau karena nyakitin aku?”
Dia diam. Kali ini, aku tahu, dia benar-benar bingung.
Hari-hari berikutnya, Dewa berusaha keras. Ia berhenti merokok, mulai terapi pernikahan, bahkan memutuskan mundur dari proyek dinas luar kota. Aku menghargai itu. Tapi kepercayaan itu seperti gelas. Sekali retak, meski disambung, airnya tak akan terasa sama.
Kami bertahan. Tapi kami bukan lagi pasangan yang sama.
Dan aku? Aku bukan lagi istri yang suka beresin koper. Karena terkadang, apa yang disembunyikan lebih baik dibiarkan busuk daripada menghancurkan segalanya saat ditemukan.
Kini, aku belajar. Bukan untuk tak percaya, tapi untuk tahu bahwa perempuan sekuat apapun tetap bisa patah—tapi juga tetap bisa memilih: apakah dia akan bangkit, atau menyeret yang menjatuhkannya ke jurang yang sama.
Aku memilih bangkit. Dengan kepala tegak. Tanpa struk, tanpa drama. Hanya aku, dan harga diriku.