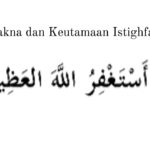Jusuf Kalla (JK) baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029. Namun, pemilihan ini tidak berjalan mulus. Agung Laksono, yang juga mengklaim sebagai calon ketua um PMI, menimbulkan kontroversi yang mengganggu awal kepemimpinan JK.
Agung Laksono, seorang tokoh senior, menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk menduduki kursi Ketua Umum PMI. Pernyataan ini langsung memicu reaksi dari JK, yang merasa posisinya terancam. Dalam menghadapi situasi ini, JK mengambil langkah tegas dengan melaporkan Agung ke pihak kepolisian.
JK tidak tinggal diam. Ia menuduh bahwa pencalonan Agung sebagai calon ketua umum PMI merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tuduhan ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara kedua pihak, dan menyoroti tantangan yang harus dihadapi JK di awal masa jabatannya.
Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang sering terjadi dalam organisasi besar seperti PMI. Dengan adanya klaim dan tuduhan, masa kepemimpinan JK diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar yang konstruktif untuk menjaga stabilitas dan fokus pada misi kemanusiaan PMI.
Kita tidak akan membahas hal ini, tapi kita akan membahas sejarah dan gerakan-gerakan PMI dan mengapa Indonesia membutuhkan PMI.
Pada tanggal 17 September 1945, hanya sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah organisasi yang akan menjadi pilar penting dalam upaya kemanusiaan di tanah air resmi didirikan. Palang Merah Indonesia (PMI), yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, lahir di tengah semangat perjuangan bangsa. Sejak saat itu, tanggal ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia, dan pada tahun 2024, PMI merayakan usia ke-79 tahun dengan berbagai karya yang tak ternilai bagi masyarakat.
Menghadapi Tantangan di Tengah Pandemi
Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia. Di tengah perjuangan melawan pandemi Covid-19, bencana alam datang silih berganti, menambah beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dari banjir yang melanda Jombang, Sukabumi, hingga Kalimantan Selatan, hingga erupsi gunung berapi yang mengguncang Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur, PMI hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan. Dalam waktu enam jam setelah bencana terjadi, PMI sudah siap sedia untuk melayani para korban, menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi.
Apa Itu Palang Merah Indonesia?
PMI bukan sekadar organisasi; ia adalah simbol harapan dan pertolongan bagi banyak orang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU 1/2018, PMI berfokus pada karya kemanusiaan tanpa memihak pada kelompok politik, ras, etnis, atau agama tertentu. Kebutuhan masyarakat adalah prioritas utama PMI, dan prinsip ketidakberpihakan ini merupakan salah satu dari Tujuh Prinsip Dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Ketujuh prinsip tersebut meliputi kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan oleh PMI.
Pelayanan PMI: Lebih dari Sekadar Donor Darah
Meskipun donor darah sering kali menjadi hal pertama yang terlintas dalam benak orang ketika mendengar PMI, layanan yang diberikan jauh lebih luas. PMI memiliki lima kategori pelayanan kepalangmerahan yang mencakup:
-
Penanganan Bencana: PMI memberikan layanan tanggap darurat, termasuk evakuasi, distribusi bantuan, dan dapur umum. Selain itu, mereka juga melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi dampak dan risiko bencana.
-
Pelayanan Sosial dan Kesehatan: Dalam kategori ini, PMI menyediakan Program Dukungan Psikososial (PSP) bagi korban bencana, layanan ambulan, Pertolongan Pertama (PP), dan Rumah Sakit Lapangan.
-
Karya Pembinaan Relawan dan Generasi Muda: PMI berkomitmen untuk membina generasi muda melalui pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah, Korps Sukarela (KSR), dan Tenaga Sukarela (TSR).
-
Pelayanan Transfusi Darah: PMI berupaya menyediakan darah yang aman dan berkualitas, melakukan uji saring darah, serta memberikan konseling kepada pendonor.
-
Diseminasi Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional: PMI aktif menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan dan informasi mengenai gerakan PMI serta Hukum Perikemanusiaan Internasional.
Setiap tahun, tanggal 17 September menjadi momen istimewa bagi Palang Merah Indonesia (PMI). Meskipun tidak bertepatan dengan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang diperingati setiap 8 Mei, tanggal tersebut tetap memiliki makna yang mendalam. Hari Palang Merah Internasional diperingati untuk menghormati Jean Henry Dunant, pendiri gerakan ini, yang wafat pada tanggal tersebut. Namun, meski berbeda tanggal, PMI tetap berkomitmen untuk menjalankan misi kemanusiaan yang sejalan dengan semangat global Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Jaringan Kemanusiaan Terbesar di Dunia
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah jaringan kemanusiaan terbesar di dunia, dengan misi mulia untuk meringankan penderitaan manusia, melindungi kehidupan, dan menjunjung tinggi martabat manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata dan keadaan darurat. Terdiri dari tiga komponen utama—Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah—setiap organisasi memiliki peran dan misi yang berbeda, namun tetap bergerak dalam harmoni untuk mencapai tujuan yang sama.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
ICRC adalah organ internasional yang berfokus pada perlindungan kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata. Didirikan pada tahun 1863, ICRC menjadi pionir dalam gerakan ini, mengatur dan mengkoordinasikan bantuan internasional bagi mereka yang terjebak dalam situasi kekerasan. Dengan dedikasi yang tinggi, ICRC berupaya memberikan bantuan yang diperlukan kepada para korban, menjadikannya sebagai garda terdepan dalam upaya kemanusiaan.
Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC)
Sementara itu, IFRC, yang didirikan pada tahun 1919, berperan sebagai penggerak dan fasilitator bagi aktivitas kemanusiaan di tingkat nasional. Dengan 189 Perhimpunan Nasional di seluruh dunia, IFRC mengoordinasikan upaya bantuan bagi korban bencana alam, pengungsi, dan situasi darurat kesehatan. IFRC memastikan bahwa setiap organisasi di bawah naungannya dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
Perhimpunan Nasional: PMI di Indonesia
Di Indonesia, PMI berfungsi sebagai perhimpunan nasional yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan kepalangmerahan. Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 dan dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, PMI telah menjadi simbol harapan dan pertolongan bagi masyarakat.
Lambang dan Identitas PMI
Lambang Palang Merah menjadi identitas yang melekat pada PMI. Berdasarkan UU 1/2018, lambang tersebut adalah palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak lima di atas dasar berwarna putih. Penggunaan lambang ini diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa simbol kemanusiaan ini digunakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.
Di sisi lain, pada 8 Juni 2002, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) juga dibentuk sebagai perhimpunan berbadan hukum yang memiliki misi serupa dalam karya kemanusiaan. Meskipun tidak terhubung secara langsung dengan PMI, BSMI beroperasi dengan Sembilan Prinsip Dasar yang mencakup keikhlasan, amanah, profesionalitas, dan kesemestaan.
Sejarah PMI
Masa Kolonial
Sejarah Palang Merah di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda pada 21 Oktober 1873 mendirikan organisasi Het Nederland-Indiche Rode Kruis (NIRK). NIRK ini diubah namanya menjadi Nederlands Rode Kruiz Afdeling Indie (NERKAI) pada 31 Desember 1945.
Pada tahun 1932, dr. RCL. Senduk dan Bahder Djohan bergerak memelopori upaya pendirian Palang Merah Indonesia. Proposal diajukan kepada Kongres NERKAI (1940) untuk pendirian PMI, akan tetapi proposal tersebut ditolak. Proposal bahkan ditanggapi oleh seorang peserta kongres dengan kata-kata sinis, “de Inlander weet niet wat menschelijk is (orang pribumi tidak mengetahui apa yang dimaksud kemanusiaan).” Proposal ini kembali diajukan pada saat Jepang masuk menguasai Hindia-Belanda pada tahun 1942–1945, tetapi usulan tersebut kembali mendapat penolakan.
Masa Revolusi Kemerdekaan dan Republik Indonesia Serikat
Pada 3 September 1945, tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno memandatkan pendirian Badan Palang Merah Nasional kepada Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan Negara Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah fakta nyata.
Berdasarkan perintah tersebut, pada 5 September 1945 dr. Buntaran membentuk Panitia Lima yang terdiri atas dr. R. Mochtar, dr. Bahder Johan, dr. Joehana, Dr. Marjuki, dan dr. Sitanala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah Indonesia.
Cita-cita tersebut terwujud pada 17 September 1945 dengan dibentuknya Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI). Ketua pertama Pengurus Besar PMI ini adalah Drs. Mohammad Hatta dan dr. R. Boentaran Martoatmodjo menjadi wakilnya.
PMI yang baru lahir ini tidak memiliki modal dan aset yang besar untuk menjalankan tugas kemanusiaannya pada waktu Perang Kemerdekaan dan akhir Perang Dunia Kedua ini. Pembiayaan organisasi lantas diusahakan secara gotong-royong dari kesukarelaan masyarakat. Dr. Kwa Tjoen Sioe membentuk panitia penderma khusus yang setiap minggunya mengumpulkan dana untuk karya PMI.
PMI waktu itu berperan penting dalam karya kemanusiaan pada masa perang, yakni dalam pembebasan dan pengembalian tawanan-tawanan perang dan pekerja paksa romusha dari masa pendudukan Jepang. Pada waktu itu, PMI tergabung dalam Organisasi Panitia Oentoek Pengembalian Djepang dan Allied Prisoneer War and Interneer (POPDA) yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudibyo dan Jenderal Mayor Adul Kadir. PMI dalam hal ini menolong orang-orang yang diangkut dari kamp-kamp internir, pengungsian anak-anak Indo-Belanda dan pengangkutan tentara Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL) ke daerah yang diduduki tentara Hindia Belanda, membantu Tentara Rakyat Indonesia dan keluarganya berpindah ke daerah Republik, serta membantu mengirimkan berita keluarga dengan formulir palang merah, kartu pos palang merah, dan berita radio.
Tidak hanya itu, PMI juga berperan dalam hubungan antarkelompok bahkan hubungan antarnegara mengingat saat itu Indonesia belum mendapatkan pengakuan diplomatik dari banyak negara. Hal ini dikarenakan citra internasional PMI yang mendapat kepercayaan dari banyak pihak. Bantuan-bantuan dari luar negeri seperti obat-obatan berhasil disalurkan kepada masyarakat melalui karya PMI. Contohnya adalah penyaluran obat-obatan bantuan dari luar negeri yang berdatangan setelah agresi militer pertama yang dilakukan Belanda pada 21 Juli 1947 dengan penyerangan ke pusat-pusat perekonomian Indonesia di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera.
Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Pemerintah Belanda pada Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, PMI mengadakan kerja sama dengan Palang Merah Hindia Belanda, NERKAI, untuk koordinasi karya kepalangmerahan di Indonesia. Hal ini sempat mendapatkan tentangan dari kelompok progresif di Indonesia.
Beberapa bulan setelahnya, pada 16 Januari 1950, guna mempersatukan gerakan Palang Merah di Indonesia, Pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI. Penyerahan ini diwakili oleh dr. B. van Trich dari pihak NERKAI dan dr. Bahder Djohan dari pihak PMI.
Pemerintah Republik Indonesia Serikat melalui Presiden Soekarno mengukuhkan organisasi PMI dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tanggal 16 Januari 1950 dan Keputusan Presiden Nomor 246 Tanggal 29 November 1963. Dokumen Keppres 25/1950 tersebut membuat PMI menjadi badan hukum bernama “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” dan PMI menjadi satu-satunya organisasi yang mengelola karya kepalangmerahan di Indonesia. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa tugas utama PMI adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949.
PMI akhirnya mendapatkan pengakuan dari Komite Palang Merah Internasional (The International Committee of the Red Cross – ICRC) pada 15 Juni 1950. Pada 16 Oktober 1950, PMI lantas diterima sebagai anggota ke-68 dalam Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang kini bernama Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC).
Selanjutnya, dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ditetapkan empat konvensi, yakni Konvensi tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Darat, Konvensi tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota Yang Luka, Sakit dan Korban-korban Karam dari Angkatan Perang di Laut, Konvensi tentang Perlakuan Tawanan Perang, dan Konvensi tentang Perlindungan Rakyat Sipil dalam Masa Perang. Konvensi ini menjadi salah satu pijakan hukum internasional bagi pelayanan Palang Merah Internasional. Pemerintah Indonesia meratifikasi seluruh konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
Masa Orde Baru
Pada 16 Desember 1985, gedung markas PMI di Jalan Gatot Soebroto Kaveling 96 Jakarta Selatan yang baru selesai dibangun diresmikan. Peresmian itu dilakukan oleh Presiden Soeharto beserta Presiden Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Enrique de la Mata. Ketua PMI pada waktu itu adalah dr. H. Suyoso Soemodimedjo.
Sebelum kantor pusat ini dibangun, markas PMI sempat berpindah-pindah. Mulai dari menumpang di Hotel Majapahit pada waktu awal pendirian PMI (waktu itu bernama Hotel du Pavillion) di Jalan Setjodiningratan dan Jalan Gondokusuman di Yogyakarta ketika ibu kota RI dipindah ke Yogyakarta, di Jalan dr. Soetomo di Jakarta Pusat, hingga di sebuah kantor yang dipakai bersama dengan suatu perusahaan kayu di Jalan Abdul Muis pada tahun 1953.
Tiga persoalan yang banyak dihadapi PMI pada masa Orde Baru ini adalah pembiayaan pelayanan, praktik calo darah yang marak terjadi, serta tingkat donor sukarela yang masih rendah.
PMI berupaya untuk memberikan pelayanan cuma-cuma untuk semua orang, terlebih pada saat terjadi bencana. Akan tetapi, untuk pelayanan donor darah, PMI menghadapi kesulitan karena tingginya biaya penyediaan layanan ini, baik dari proses tranfusinya, penyimpanan darahnya, hingga distribusi darah tersebut. Situasi finansial yang sulit ini juga dihadapi PMI untuk dapat membiayai para pekerjanya dan pelatihan sukarelawan karena dana dari APBN dan APBD yang terbatas.
Di samping itu, tingginya permintaan darah dan kurangnya pasokan darah yang bisa disediakan PMI dalam segala keterbatasannya memunculkan fenomena calo darah. Pada waktu itu, di rumah-rumah sakit dapat ditemui orang yang menjajakan darah untuk pasien-pasien. Hal ini berlawanan dengan prinsip yang dipegang PMI bahwa darah bukanlah komoditas yang boleh diperjualbelikan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Namun nyatanya, kurangnya suplai darah membuat fenomena tersebut menjadi susah untuk dihindari.
PMI pada masa itu juga menghadapi rendahnya tingkat donor sukarela. Donor sukarela adalah donor yang dibuat oleh seseorang tanpa adanya pasien penerima yang telah ditentukan oleh pendonor. Yang terakhir itu disebut sebagai donor pengganti. Donor sukarela ini diperlukan untuk mengatasi kebutuhan transfusi darah.
Pada tahun 1969 misalnya, PMI mencatat jumlah penerima darah sebanyak 28.265 labu darah kapasitas 200 cc. Padahal, pada tahun tersebut hanya terdapat 6.859 donor sukarela. Selebihnya, sejumlah 21.406 labu darah, adalah donor pengganti, entah dari keluarga dan kerabat maupun dari calo darah.
Dengan beragam upaya promosi peningkatan kesadaran masyarakat, pada tahun 1981 angka donor sukarela meningkat menjadi 198.821 donor sukarela, dengan angka donor pengganti sejumlah 64.835 donor pengganti. Direktur Lembaga Pusat Transfusi Darah PMI, dr. Masri Roestam, waktu itu menyebutkan bahwa keberhasilan peningkatan donor sukarela sesuai dengan Prinsip Dasar PMI dan akan membantu mengatasi masalah jual-beli darah yang terjadi.
Akan tetapi, ketersediaan darah masih belum merata di berbagai daerah. Sebagai contoh, pada tahun 1981, di PMI Medan tercatat bahwa donor darah dari Kota Medan hanya dapat memenuhi lima persen dari total kebutuhan darah di kota tersebut. Tantangan biaya, fenomena calo darah, dan tingkat donor sukarela menjadi ketiga tantangan yang fokus dihadapi PMI pada masa Orde Baru.
Masa Reformasi
Pada 4 Februari 2011, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. PP ini mengatur tentang pelayanan transfusi darah yang merupakan salah satu pelayanan PMI. Pelayanan ini dikoordinasi oleh Unit Transfusi Darah (UTD) PMI di seluruh Indonesia. Peraturan ini mengubah peraturan lama pada PP 18/1980 guna meningkatkan mekanisme pelayanan transfusi darah di Indonesia.
Kemudian pada 9 Januari 2018, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. UU 1/2018 ini menetapkan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum dan bertujuan untuk mencegah, meringankan penderitaan, dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa keberpihakan pada kelompok agama, ras, etnis, gender, dan politik tertentu. UU ini mengukuhkan PMI sebagai organisasi yang berkarya untuk kemanusiaan di Indonesia.
Demikianlah artikel yang cukup panjang mengenai PMI.