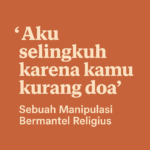Hari Sabtu kemarin, aku ketemu dengan temanku. Usianya sekitar 35 tahun, seorang ayah dari dua anak. Kami duduk cukup lama di sebuah warung kopi kecil, membicarakan banyak hal. Dari pekerjaan, anak-anak, sampai urusan rumah tangga.
Di tengah obrolan itu, dia tiba-tiba berkata, “Pak, saya akhir-akhir ini baru sadar, ternyata saya sering salah sangka sama istri.”
Aku mengernyit sedikit, penasaran ke mana arah pembicaraan ini. Lalu dia mulai bercerita.
“Beberapa waktu lalu, saya lihat istri saya duduk di sofa, pegang HP lama sambil senyum-senyum sendiri. Dari jauh, kelihatannya kayak lagi menikmati waktu luangnya. Saya sempat berpikir, ‘Wah, akhirnya dia punya me-time juga.’ Tapi ternyata saya salah besar.”
Dia menghela napas pelan sebelum melanjutkan.
“Kelihatannya memang kayak santai. Scroll Instagram, buka YouTube, bales WA. Tapi ternyata itu bukan hiburan. Bukan pelarian. Itu bentuk kerja yang nggak kelihatan.”
Aku diam, mendengarkan. Lalu dia cerita tentang satu kejadian yang membekas di hatinya.
“Waktu itu, anak kami, Naura, lagi ngajak main. Tapi istri saya tetap fokus ke HP-nya. Saya yang baru pulang kerja, lelah, dan mungkin sedang sensitif, langsung menegur, ‘Bu, anak kamu ngajak main tuh,’ dengan nada yang agak tinggi. Saya merasa benar saat itu. Merasa sedang mengingatkan. Tapi dia hanya diam. Menghela napas. Tidak menjawab.”
Ia sempat menunduk sebelum melanjutkan.
“Malamnya, setelah anak-anak tidur dan suasana rumah tenang, dia baru cerita. Ternyata waktu yang saya kira dia habiskan untuk bersantai itu, dia justru sedang cari referensi MPASI buat Naura. Lagi lihat testimoni diapers karena anak kami satunya lagi ruam. Sekalian balas WA dari kantor. Bahkan sempat buka marketplace buat cek promo kebutuhan dapur.”
“Saya kira dia lagi scrolling buat hiburan. Ternyata dia sedang berusaha jadi ibu, dan di saat yang sama tetap jadi manusia yang mengingat semua.”
Kalimat itu membuatku diam cukup lama.
“Dan sering kali, itu semua dia lakukan di jam yang seharusnya jadi waktu istirahat. Jam 9 malam ke atas. Setelah anak-anak tidur. Saat saya sudah bisa selonjoran, dia baru mulai ‘kerja shift malam’.”
Aku mengangguk pelan. Aku tahu persis maksudnya.
“Buat istri, me-time itu bukan soal pegang HP. Tapi soal apa yang sedang dia pikirkan saat pegang HP. Kalau pikirannya masih muter soal to-do list, kebutuhan anak, rumah tangga, ya badannya juga nggak benar-benar istirahat.”
Aku menatapnya. Dia terlihat tulus.
“Dan saya sadar, saya sering nggak peka. Saya pikir dia lagi santai. Padahal yang dia butuhkan bukan cuma waktu luang, tapi beban yang dibagi.”
Sejak itu, katanya, dia mulai mencoba berubah. Tidak menunggu istrinya bilang capek dulu, baru membantu. Tapi belajar ikut ambil bagian sejak awal.
“Sekarang kalau lauk habis, saya yang siapkan makan siang anak. Saya yang cek kebutuhan rumah. Urusan pakaian dan sebagian dapur juga saya bantu. Memang belum sempurna, tapi saya berusaha.”
Lalu ia berkata dengan nada yang dalam, “Saya belajar mengingat, kadang yang istri butuhkan bukan pelukan di akhir hari… tapi pasangan yang ikut memikul beban sejak pagi.”
Kami terdiam sejenak.
Aku pulang sore itu dengan hati yang penuh. Bukan karena nasihat, tapi karena pengakuan jujur seorang ayah muda yang sedang belajar menjadi suami yang lebih peka.
Dan aku pun jadi berpikir… mungkin banyak dari kita para suami pernah melakukan hal yang sama. Melihat istri duduk sambil pegang HP, lalu mengira itu waktu santainya. Padahal bisa jadi, itu justru momen dia sedang bekerja paling keras — hanya saja tanpa seragam, tanpa ruang kantor, tanpa tanda tangan.
Kadang yang mereka butuhkan bukan waktu kosong, tapi ditemani. Bukan dibebaskan dari beban, tapi diajak berbagi.